

Welcome
Please enter your email and password to access your personal account.
Do not have account? Register
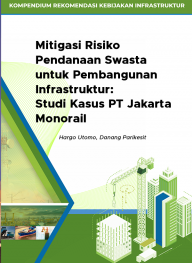
Chapter 5
Mitigasi Risiko Pendanaan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus: PT Jakarta Monorail
Pembangunan kereta listrik monorel di Jakarta menandai langkah penting dalam adopsi sistem transportasi massal perkotaan berbasis pendanaan swasta murni (private equity financing). Proyek ini tidak hanya bertujuan mengatasi kemacetan lalu lintas, tetapi juga menggambarkan peran strategis sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. Studi kasus PT Jakarta Monorail (PT-JM) memperlihatkan bagaimana entitas swasta menghadapi kompleksitas pengelolaan risiko mulai dari tahap inisiasi hingga operasionalisasi proyek. Dalam skema ini, tantangan utama muncul dari ketidakseimbangan antara kepentingan investor dalam memperoleh imbal hasil vis-à-vis harapan publik atas tarif yang terjangkau dan pelayanan yang andal. Pemetaan risiko secara menyeluruh, termasuk penguasaan lahan, proyeksi pasar properti, serta sensitivitas harga tiket menjadi faktor krusial dalam pembangunan infrastruktur transportasi berbasis pendanaan swasta murni. Dalam situasi ini, pemerintah tetap memegang tanggung jawab utama untuk menjamin keberlanjutan proyek sekaligus melindungi kepentingan publik, terutama melalui kebijakan tata ruang dan regulasi jaminan risiko. Artikel ini menyimpulkan pentingnya manajemen kelembagaan yang kuat, keterlibatan bank nasional, dan skema mitigasi risiko yang menyeluruh untuk mendukung keterlibatan swasta dalam pembiayaan infrastruktur di masa depan.
Mitigasi Risiko Pendanaan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus: PT Jakarta Monorail
Other Chapters
Chapter 1 : Alokasi Risiko dalam Proyek KPS: Studi Kasus Proyek Terminal Bus Antarkota di Giwangan Yogyakarta
Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan skema strategis dalam penyediaan infrastruktur publik. Meski demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan dan alokasi risiko yang tepat. Studi kasus Terminal Bus Giwangan di Yogyakarta mengungkap kegagalan implementasi alokasi risiko dalam proyek KPS. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk pembangunan dan pengelolaan terminal, tetapi gagal memenuhi proyeksi permintaan akibat lemahnya pengendalian terhadap terminal liar dan minimnya koordinasi antarpemerintah daerah. Akibatnya, investor mengalami kerugian besar hingga proyek dihentikan sebelum masa konsesi berakhir. Artikel ini menunjukkan bahwa risiko permintaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab publik tidak dikelola dengan baik. Kasus ini berbeda dengan apa yang terjadi di Terminal Amritsar dan Dehradun di India, di mana skema KPS cukup sukses diterapkan karena adanya komitmen pemerintah dalam menjamin trayek dan pengguna jasa terminal. Artikel ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan untuk memperbaiki implementasi KPS di Indonesia: penguatan kerangka hukum alokasi risiko, fleksibilitas dalam renegosiasi kontrak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan mengelola dinamika kerja sama investasi. Tanpa reformasi tersebut, skema KPS berisiko merugikan kedua belah pihak dan gagal mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
AuthorDanang ParikesitSulistyowatiRizky WirastomoDownloadAlokasi Risiko dalam Proyek KPS: Studi Kasus Proyek Terminal Bus Antarkota di Giwangan Yogyakarta
PDF File. 1005 KB 3 DownloadRegister To DownloadChapter 2 : Optimalisasi Kapasitas Lembaga Terkait dalam Rangka Mitigasi Risiko Proyek KPS Air Minum dengan Tinjauan Risiko Ketersediaan Air Baku: Studi Kasus Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pemerintah Kabupaten Tangerang
Penyediaan air minum yang andal menjadi tantangan besar dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS), terutama karena tingginya risiko terhadap ketersediaan air baku. Risiko ini mencakup kontinuitas, kuantitas, dan kualitas air baku yang sangat memengaruhi keberhasilan proyek KPS air minum. Studi kasus di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa persoalan teknis dan nonteknis, termasuk ketidakpastian sumber air dan koordinasi lintas wilayah, menjadi hambatan signifikan bagi pelaku usaha. Ketidakterpaduan kelembagaan dan lemahnya kepastian hukum memperbesar keraguan investor swasta. Artikel ini menekankan pentingnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai front-liner mitigasi risiko teknis air baku dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) dalam menangani konflik nonteknis. BBWS dapat berperan sebagai penjamin keberlanjutan air sungai melalui pemanfaatan perangkat seperti neraca air dan Pola Operasi Waduk dan Alokasi Air (POWAA), sementara BPPSPAM diharapkan berfokus pada upaya mediasi antarwilayah. Adanya kebijakan yang memadai dari lembaga-lembaga terkait sangatlah diperlukan, termasuk memperkuat kapasitas BBWS dan BPPSPAM agar PT PII maupun PJPK memiliki mitra yang jelas dalam proses penilaian aplikasi dan pemberian penjaminan infrastruktur SPAM.
AuthorSulistyowatiRizky WirastomoAries F. FirmanAnanto Darudono PutroDownloadOptimalisasi Kapasitas Lembaga Terkait dalam Rangka Mitigasi Risiko Proyek KPS Air Minum dengan Tinjauan Risiko Ketersediaan Air Baku: Studi Kasus Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pemerintah Kabupaten Tangerang
PDF File. 1 MB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 3 : Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Infrastruktur di Indonesia: Studi Kasus Jalan Tol Kanci-Pejagan
Tulisan ini mengkaji dinamika pengadaan tanah melalui studi kasus pembangunan Jalan Tol Kanci–Pejagan yang menunjukkan keberhasilan pendekatan alternatif oleh PT Semesta Marga Raya. Pengadaan tanah sendiri hampir selalu menjadi tantangan utama dalam program pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun, kasus pembangunan Jalan Tol Kanci–Pejagan justru menggambarkan bagaimana keterlibatan aktif pihak swasta dalam pembebasan lahan, sebelum diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2012, mampu mempercepat proses pembangunan tanpa mengorbankan aspek sosial masyarakat. Artikel ini mengulas pula perubahan regulasi yang membatasi peran swasta secara langsung dalam pengadaan tanah serta menawarkan paradigma baru dalam perencanaan ruang dan kompensasi. Penulis menekankan pentingnya kepastian tata ruang, pengelolaan kelembagaan, serta keadilan dalam pemberian kompensasi pada pemilik tanah serta merekomendasikan perlunya koordinasi yang lebih baik antarinstansi, reformasi kelembagaan seperti BPN, serta perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Dengan analisis menyeluruh terhadap aspek hukum, sosial, dan teknis, artikel ini dapat menjadi rujukan penting dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah yang efisien dan adil demi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
AuthorTri TjahjonoNurhasan IsmailDownloadPengadaan Tanah bagi Pengembangan Infrastruktur di Indonesia: Studi Kasus Jalan Tol Kanci-Pejagan
PDF File. 994 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 4 : Penugasan BUMN sebagai PJPK untuk Proyek KPS: Studi Kasus Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia menghadapi tantangan kapasitas institusional Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), khususnya pada proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Salah satu pendekatan strategis yang diambil adalah penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PJPK. Studi kasus pembangunan Terminal Kalibaru oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengilustrasikan bagaimana penugasan ini mampu mendorong efisiensi dan inovasi, khususnya dalam pembiayaan infrastruktur dan manajemen teknologi. Namun, penugasan tersebut juga menimbulkan implikasi kebijakan, mulai dari tata kelola tarif, risiko regulasi, hingga tantangan akuntabilitas antarlembaga BUMN. Terdapat pula kekhawatiran akan potensi dominasi pasar oleh BUMN yang dapat menghambat iklim persaingan usaha. Artikel ini merekomendasikan penerapan strategi “jalur ganda” untuk mendesain proyek KPS secara paket, guna membedakan antara pasar BUMN dan pasar kompetisi penuh. Strategi ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan kecepatan pembangunan infrastruktur (deliverability) dan prinsip keterbukaan pasar (contestability), serta menjadi kerangka kebijakan untuk memperjelas peran BUMN sebagai PJPK. Dengan demikian, BUMN dapat berkontribusi optimal sebagai katalis pembangunan tanpa mengorbankan prinsip tata kelola yang sehat dan keberlanjutan investasi.
AuthorDanang ParikesitKawik SugianaDownloadPenugasan BUMN sebagai PJPK untuk Proyek KPS: Studi Kasus Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PDF File. 845 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 6 : Mitigasi Risiko Utang untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan MRT Jakarta
Penggunaan utang luar negeri berjangka panjang dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, seperti pada proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, memiliki peluang sekaligus risiko yang perlu dimitigasi secara cermat. Artikel ini membahas kerangka kelembagaan, kebijakan, dan pembelajaran yang relevan untuk menyeimbangkan manfaat pembiayaan (atau peluang) dengan potensi beban (atau risiko) jangka panjang. Meskipun pinjaman lunak dari lembaga donor seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) menawarkan suku bunga rendah dan tenor panjang, terdapat risiko finansial, operasional, dan politik yang dapat berdampak pada keberlanjutan proyek. Melalui studi kasus MRT Jakarta, artikel ini mengkaji pentingnya tata kelola utang yang baik, keberadaan lembaga pengelola utang daerah, dan peran pemerintah sebagai penjamin risiko. Selain itu, artikel juga mengulas keterkaitan antara tarif layanan publik dan keberlanjutan finansial proyek, serta strategi mitigasi risiko investasi yang dapat dilakukan melalui kerangka kelembagaan dan alokasi risiko yang proporsional. Di bagian akhir artikel, penulis menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal, partisipasi sektor swasta, dan kejelasan peran antarpemangku kepentingan untuk menghindari jebakan utang dan mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.
AuthorDanang ParikesitHargo UtomoDownloadMitigasi Risiko Utang untuk Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan MRT Jakarta
PDF File. 847 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 7 : Peluang Investasi di Sektor Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus PLTU Batang di Jawa Tengah
Kebutuhan energi listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, populasi, dan rasio elektrifikasi. Untuk mengatasi potensi krisis pasokan dan ketergantungan pada energi fosil, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuka peluang investasi sektor ketenagalistrikan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Studi kasus PLTU Batang menunjukkan bahwa partisipasi swasta dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam pembangunan infrastruktur energi. Payung hukum yang mendukung hal ini antara lain UUD 1945 pasca-amandemen serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kebijakan ini dapat membuka kran partisipasi investor, meskipun masih terdapat dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT PLN. Untuk menjamin keberlanjutan energi, pemerintah juga perlu mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan, khususnya panas bumi, yang memiliki potensi besar di Indonesia. Meski demikian, tantangan regulasi, sentralisasi peran PLN, dan kurangnya kompetisi masih menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, pemerintah perlu mereformulasi kebijakan desentralisasi ketenagalistrikan berbasis otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Penguatan regulasi dan amandemen undang-undang secara menyeluruh menjadi prasyarat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, adil, dan efisien. Dengan langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan energi sekaligus mengundang lebih banyak investasi swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
AuthorTri HayatiDjoni HartonoDownloadPeluang Investasi di Sektor Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus PLTU Batang di Jawa Tengah
PDF File. 738 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 8 : Reposisi BUMD Pengelola Sanitasi menuju Kota Berketahanan: Studi Kasus DKI Jakarta
Kondisi sanitasi DKI Jakarta masih jauh dari ideal – untuk tidak menyebutnya ‘memprihatinkan’ – dengan hanya sebagian kecil penduduk terlayani oleh sistem pengolahan limbah yang memadai. Rendahnya cakupan layanan menyebabkan pencemaran lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pemerintah telah menargetkan peningkatan layanan sanitasi melalui tiga strategi utama, yaitu pembangunan sistem IPAL terpusat, pengembangan IPAL komunal, dan optimalisasi tangki septik. Namun, terdapat celah layanan sebesar 17% yang memerlukan intervensi khusus melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Untuk mendukung strategi ini, reposisi lembaga pengelola sanitasi sangatlah krusial, dengan menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola aset yang bertugas menjalin kemitraan dengan para investor. BUMD dinilai memiliki peran strategis karena mampu mengakses pembiayaan, mengelola aset secara langsung, dan bertindak sebagai pelaksana teknis. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan pengelolaan sanitasi yang baik. Selain itu, peningkatan layanan sanitasi melalui edukasi, insentif, regulasi, dan integrasi kebijakan perlu dilakukan agar sanitasi tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan sekunder, namun kebutuhan primer seluruh warga masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan, pembenahan kebijakan tarif, dan dukungan pemerintah, pembangunan sistem sanitasi dapat menunjang terwujudnya kota yang tangguh dan berketahanan (resilient city).
AuthorCindy Rianti PriadiSetyo Sarwanto MoersidikMuhammad Halley YudhistiraDownloadReposisi BUMD Pengelola Sanitasi menuju Kota Berketahanan: Studi Kasus DKI Jakarta
PDF File. 697 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 9 : Best Practice Penerapan Track Access Charge (TAC) untuk Indonesia
Meningkatnya minat masyarakat dan perhatian pemerintah terhadap moda transportasi Kereta Api (KA) menuntut adanya kebijakan pembiayaan yang lebih adil dan efisien, khususnya terkait Track Access Charge (TAC). TAC merupakan biaya yang dibebankan kepada operator atas penggunaan jalur rel milik negara. Biaya ini kemudian digunakan untuk mendanai pemeliharaan, pengembangan, serta investasi prasarana KA. Namun dalam praktiknya, perhitungan TAC dinilai belum sepenuhnya adil karena tidak mempertimbangkan frekuensi pemakaian jalur dan tidak menerapkan prinsip pengurangan atas biaya operasional dan pemeliharaan (net-off). Belum adanya pemisahan yang jelas antara aset negara dan aset operator, seperti dalam kasus jalur KA Kertapati–Muara Enim, semakin memperumit tata kelola dan perhitungan pembiayaan TAC. Oleh sebab itu, kebijakan TAC perlu direformulasi dengan mempertimbangkan eksternalitas positif angkutan KA serta membedakan antara layanan KA komersial dan nonkomersial. Pemerintah juga harus mempromosikan secara aktif penggunaan KA untuk angkutan barang guna mengurangi beban jalan raya. Ke depan, pelibatan pihak swasta melalui skema Public-Private Partnership dapat menjadi opsi strategis untuk memperluas layanan KA, dengan tetap mengedepankan intervensi negara dalam penyediaan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan terlayani dengan fasilitas perkeretaapian.
AuthorTri TjahjonoNuzul AchjarDownloadBest Practice Penerapan Track Access Charge (TAC) untuk Indonesia
PDF File. 769 KB 1 DownloadRegister To DownloadChapter 10 : Risiko Investasi Pembangunan Jalan Tol dengan Perkiraan Lalu Lintas Rendah
Pembangunan jalan tol merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema user pay principle. Meski menawarkan potensi investasi yang besar, proyek jalan tol juga dihadapkan pada berbagai risiko, khususnya pada ruas-ruas dengan proyeksi lalu lintas rendah. Artikel ini menguraikan risiko-risiko utama dalam pembangunan jalan tol, mulai dari tahap perencanaan, konstruksi, hingga operasional, termasuk risiko pembebasan lahan, pendanaan, konstruksi, dan volume lalu lintas. Artikel ini juga menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko yang sistematis dan respons yang tepat, baik melalui mitigasi, transfer, penghindaran, maupun penerimaan risiko. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa pembebasan lahan, subsidi modal, jaminan pendapatan minimum, serta insentif fiskal seperti pembebasan pajak. Selain itu, kajian-kajian lebih lanjut mengenai alternatif kebijakan (seperti shadow toll dan clawback principle yang telah diterapkan di negara lain) perlu terus dilakukan. Skema Public-Private Partnership (PPP) yang diimbangi dengan kebijakan dukungan pemerintah diharapkan mampu mempercepat pembangunan jalan tol yang menarik bagi investor, terutama pada ruas-ruas dengan kelayakan finansial terbatas.
AuthorRudy Hermawan KarsamanMirayanti SaidDownloadRisiko Investasi Pembangunan Jalan Tol dengan Perkiraan Lalu Lintas Rendah
PDF File. 534 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 11 : Rekonstruksi Pungutan Negara atas Infrastruktur Telekomunikasi
Infrastruktur telekomunikasi memiliki peran strategis dalam membangun konektivitas nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menunjang berbagai sektor kehidupan. Namun, upaya percepatan pembangunan sektor ini kerap terkendala oleh tumpang tindih pungutan negara yang tidak selaras dengan insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah. Artikel ini menyoroti pentingnya rekonstruksi kebijakan pungutan negara atas infrastruktur telekomunikasi agar menjadi lebih sederhana, terprediksi, dan diterima secara politik. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNPB) dan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), berbagai pungutan baru bermunculan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan beban biaya yang tidak proporsional bagi pelaku usaha. Artikel ini juga mengulas dampak negatif dari ‘pseudo tax’ dalam bentuk PNBP tanpa instrumen formal seperti yang jamak berlaku dalam sistem perpajakan. Untuk itu, penulis menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antarkementerian dan lembaga serta peninjauan ulang terhadap regulasi yang berpotensi mengganggu iklim investasi. Penulis juga merekomendasikan reformasi sistem PNBP, pelaksanaan Pasal 3 UU PNBP secara konsisten, serta penguatan koneksi antara pungutan negara dan pelayanan publik guna membangun legitimasi fiskal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam memperbaiki infrastruktur dan layanan telekomunikasi.
AuthorHaula RosdianaEdi Slamet IriantoDownloadRekonstruksi Pungutan Negara atas Infrastruktur Telekomunikasi
PDF File. 588 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 12 : Aspek Pembiayaan pada Pembangunan Bandar Udara
Keterbatasan kapasitas fiskal mendorong perlunya kebijakan pembiayaan baru dalam pembangunan bandar udara di Indonesia, mengingat sebagian besar pembangunan masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan terbukanya peluang partisipasi swasta, strategi pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau swasta murni perlu dirancang secara komprehensif. Studi kasus Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menunjukkan kompleksitas pembiayaan antara APBN, APBD, dan pihak ketiga, termasuk pembentukan PT BIJB sebagai badan usaha pengelola. Pembangunan kawasan aerocity seluas 5.000 hektare menjadi bagian integral dalam menciptakan ekosistem bandar udara yang lebih produktif. Untuk mengoptimalkan pembiayaan, pemerintah perlu menetapkan sumber pendapatan seperti Passenger Service Charge (PSC), menyusun rencana bisnis untuk pengelolaan bandara UPT, serta mengembangkan sektor non-aeronautika seperti logistik dan kargo. Kawasan bandara diharapkan tidak hanya menjadi simpul transportasi, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi regional. Agar strategi ini dapat dijalankan dengan efektif, pemerintah perlu merancang regulasi operasional yang melibatkan Pemda dan memperluas cakupan pendapatan hingga luar batas fisik bandara. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik investasi sekaligus memperbesar kontribusi ekonomi dari sektor kebandarudaraan secara nasional.
AuthorBasauli Umar LubisDownload
Kompendium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) 1 - 12
Author by IIGF Institute