

Welcome
Please enter your email and password to access your personal account.
Do not have account? Register
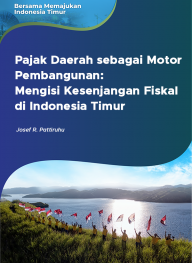
Chapter 6
Pajak Daerah sebagai Motor Pembangunan: Mengisi Kesenjangan Fiskal di Indonesia Timur
Artikel ini membahas peran strategis pajak daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mereduksi kesenjangan fiskal di Indonesia Timur, khususnya Provinsi Maluku. Di tengah tantangan disparitas pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia, pajak daerah dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Artikel ini menyoroti tiga sektor unggulan—perikanan dan kelautan, perdagangan dan industri, serta pariwisata—yang memiliki potensi besar di kawasan timur Indonesia namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil analisis SWOT terhadap faktor internal dan eksternal penerimaan pajak daerah menunjukkan posisi strategis Provinsi Maluku dalam kuadran agresif. Artinya, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan dengan mengandalkan kekuatan internal daerah. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya penguatan strategi dan kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal, koordinasi lintas sektor, serta integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi penguatan infrastruktur, digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi sinergi lintas sektor. Dengan pendekatan komprehensif ini, pajak daerah dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
Pajak Daerah sebagai Motor Pembangunan: Mengisi Kesenjangan Fiskal di Indonesia Timur
Other Chapters
Chapter 1 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur dengan Pendanaan Kreatif
Artikel yang merupakan prolog buku “Bersama Memajukan Indonesia Timur: Membangun Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif melalui Skema Pembiayaan Kreatif” ini memberikan ulasan umum mengenai strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur (KIT), yang mencakup Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Meskipun kawasan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kesenjangan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dengan Kawasan Indonesia Barat (KIB) masih cukup signifikan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, pemerintah perlu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif. Artikel ini mengeksplorasi berbagai pendekatan pembiayaan, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), thematic bond, green financing, dan blended finance, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Di samping itu, penulis juga membahas beberapa aspek tata kelola fiskal daerah, seperti optimalisasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, serta reformasi kebijakan transfer ke daerah. Penekanan pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di KIT. Dengan pendekatan terpadu ini, KIT berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan mencapai pembangunan yang merata antarwilayah.
AuthorAnton Abdul FatahYuki M.A. WardhanaRatna WidianingrumAndreas WibowoHermawanRoihans Muhammad IqbalDownloadMewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur dengan Pendanaan Kreatif
PDF File. 313 KB 1 DownloadRegister To DownloadChapter 2 : Membuka Peluang Daerah dalam Memenuhi Kebutuhan Pendanaan untuk Percepatan Pembangunan di Maluku dan Papua menuju Indonesia Emas 2045
Pembangunan wilayah yang berkeadilan menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, terutama melalui percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya di Maluku dan Papua. Artikel ini mengidentifikasi kesenjangan pembangunan yang masih signifikan, antara lain dalam aspek kualitas sumber daya manusia, akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan analisis proyeksi hingga tahun 2045, wilayah Maluku dan Papua diperkirakan belum akan mencapai target-target nasional apabila hanya mengandalkan pendanaan konvensional. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merancang model pembiayaan alternatif yang inovatif dan inklusif untuk mempercepat transformasi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Beberapa skema yang diusulkan meliputi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi tematik, pendanaan filantropi, pembiayaan utang daerah, pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, crowdfunding, serta blended finance. Artikel ini juga menampilkan beberapa praktik baik (best practices) dari negara-negara seperti Brasil, India, dan Kenya untuk memperluas peluang mobilisasi pembiayaan nonkonvensional. Pada akhirnya, pembangunan Maluku dan Papua membutuhkan dukungan regulasi, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif sebagai strategi percepatan pembangunan wilayah yang berdaya saing tinggi.
AuthorAldy K. MardikantoNovie AndrianiHanna Tua MarinaSetiawan Eko WardhanyRamadian IrvanizarMuhammad Alwi RamadhanKhairani MardhiahFelicia Esterlita NugrohoDownloadMembuka Peluang Daerah dalam Memenuhi Kebutuhan Pendanaan untuk Percepatan Pembangunan di Maluku dan Papua menuju Indonesia Emas 2045
PDF File. 870 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 3 : Infrastruktur Dasar di Timur Indonesia: Mengejar Pembangunan Yang Berkelanjutan
Kawasan Indonesia Timur, khususnya Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua, memiliki potensi ekonomi cukup besar di sektor perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Namun, keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi potensi tersebut. Artikel ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan sebagai prasyarat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan itu. Di sektor perikanan, pengembangan pusat pengolahan ikan terpadu, pembangunan jembatan penghubung antarpulau, serta peningkatan akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya perlu dilakukan. Pada sektor pertambangan, penguatan infrastruktur jalan, pelabuhan, pasokan energi berkelanjutan, dan sistem sanitasi menjadi fokus utama. Adapun di sektor pariwisata, peningkatan aksesibilitas melalui pengembangan jalan dan bandara, serta penyediaan fasilitas wisata yang memadai, sangat dibutuhkan. Penulis merekomendasikan pengembangan infrastruktur berbasis potensi lokal dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan strategi tersebut, pembangunan di Indonesia Timur dapat lebih inklusif, berdaya saing, dan berdampak jangka panjang bagi pembangunan nasional.
AuthorSammyles G. M. AmahekaFebrino WangeanMicky KololuDownloadInfrastruktur Dasar di Timur Indonesia: Mengejar Pembangunan Yang Berkelanjutan
PDF File. 1 MB 1 DownloadRegister To DownloadChapter 4 : Hilirisasi Industri Tambang Nikel di Maluku Utara dan Dampaknya pada Sektor Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan
Hilirisasi industri tambang nikel di Maluku Utara merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri. Provinsi ini memiliki cadangan nikel terbesar kedua di Indonesia dan menjadi pusat pengembangan kawasan industri pengolahan nikel seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Hilirisasi ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui peningkatan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Namun, pengembangan industri ini juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran air dan tanah, konflik lahan, dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Artikel ini mengkaji kondisi industri nikel di Maluku Utara, potensi sumber daya, skema pembiayaan, serta proyeksi pengembangan industri hilir. Penulis mengusulkan penerapan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), penerapan teknologi rendah emisi, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendorong hilirisasi nikel di Maluku Utara. Rekomendasi kebijakan yang diajukan menekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan hasil riset, digitalisasi perizinan, dan pemberian insentif fiskal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, hilirisasi industri nikel diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial di Maluku Utara.
AuthorJohan Marcus TupanDownloadHilirisasi Industri Tambang Nikel di Maluku Utara dan Dampaknya pada Sektor Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan
PDF File. 1 MB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 5 : Skema Pembiayaan Kreatif untuk Hilirisasi Perikanan Tangkap di Maluku
Tulisan ini membahas strategi hilirisasi perikanan tangkap di Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Indonesia dalam industri perikanan global. Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar, namun kontribusinya masih terbatas pada produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah. Untuk menjawab tantangan tersebut, artikel ini menawarkan skema pembiayaan kreatif melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan industri pengolahan perikanan berbasis pelabuhan. Pendekatan ini mencakup pengembangan infrastruktur pendukung, strategi pembiayaan berbasis availability payment dan sukuk negara, serta pelibatan institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Pattimura. Artikel ini juga mengulas praktik pengelolaan industri perikanan tangkap di beberapa negara seperti Norwegia, Brasil, dan India yang berhasil menerapkan pendekatan keberlanjutan dan nilai tambah tinggi. Penulis menekankan pentingnya dukungan kelembagaan, pemetaan rantai pasok, serta penguatan kapasitas kelembagaan nelayan dalam menunjang industrialisasi berbasis sumber daya laut sehingga strategi ini dapat mempercepat transformasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.
AuthorWilma LatunyDownloadSkema Pembiayaan Kreatif untuk Hilirisasi Perikanan Tangkap di Maluku
PDF File. 1 MB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 7 : Tantangan Kebijakan dan Administrasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Konteks Kawasan Timur Indonesia
Artikel ini membahas tantangan kebijakan dan administrasi pajak daerah yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dengan fokus pada kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Melalui analisis komprehensif, artikel ini mengidentifikasi lima tantangan utama dari sisi kebijakan, termasuk kurang optimalnya rasio penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), ketidakadilan dalam penerapan struktur multitarif, potensi penyalahgunaan insentif fiskal, keterbatasan kewenangan daerah atas opsen, serta keterbatasan cakupan basis pajak di wilayah nonurban seperti KTI. Sementara itu, tantangan administratif meliputi rendahnya tingkat kepatuhan pajak, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan akses data pihak ketiga. Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis merekomendasikan tujuh langkah strategis, mulai dari perluasan basis pajak dan fleksibilitas opsen, hingga penguatan kapasitas fiskal daerah dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, penulis berusaha memberikan landasan kebijakan yang kuat guna memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal yang berkelanjutan di Indonesia.
AuthorNaranggi Pramudya SokoDownloadTantangan Kebijakan dan Administrasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Konteks Kawasan Timur Indonesia
PDF File. 499 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 8 : Optimalisasi Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dalam Mendukung Percepatan Pembangunan di Kepulauan Maluku
Optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan wilayah kepulauan seperti Maluku yang kaya akan sumber daya alam namun masih tertinggal secara ekonomi. Letak geografis Maluku yang didominasi perairan menuntut pendekatan fiskal yang adil dan sensitif terhadap karakteristik wilayah. Namun, temuan kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal nasional belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan pembangunan daerah kepulauan. Ketimpangan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)—khususnya dalam konteks sektor perikanan—menandakan belum optimalnya pengakuan atas kontribusi strategis wilayah ini. Kesenjangan tersebut berdampak langsung pada terbatasnya infrastruktur dasar, rendahnya konektivitas antarpulau, serta ketimpangan layanan publik. Oleh sebab itu, penghitungan TKD yang mengintegrasikan luasan wilayah laut dalam formula DAU dan DBH perikanan perlu segera direformulasi. Selain itu, penguatan afirmasi melalui perluasan cakupan Dana Percepatan dan optimalisasi alokasi DAK tematik juga perlu segera dilakukan. Kebijakan anggaran yang berbasis kebutuhan dan berorientasi pada keadilan spasial diyakini dapat memperkuat daya saing Maluku sebagai wilayah strategis sekaligus mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
AuthorDjufri Rays PattilouwDownloadOptimalisasi Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dalam Mendukung Percepatan Pembangunan di Kepulauan Maluku
PDF File. 757 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 9 : Optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk Mendukung Pembiayaan Pembangunan di Indonesia Timur
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan, terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih menghadapi tantangan ketimpangan fiskal dan infrastruktur. Artikel ini menyoroti bagaimana optimalisasi DBH Pajak dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah. Meskipun wilayah timur Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, ketergantungan terhadap Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum menyebabkan DBH Pajak belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, terdapat berbagai faktor, seperti rendahnya kapasitas teknis pemerintah daerah, kendala dalam rekonsiliasi fiskal, serta terbatasnya kepatuhan perpajakan, yang menghambat optimalisasi DBH Pajak. Hasil analisis menunjukkan rendahnya proporsi DBH Pajak terhadap total Transfer Ke Daerah (TKD), yang akhirnya berdampak pada terbatasnya belanja modal dan layanan publik di daerah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, penulis mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan, termasuk peningkatan kualitas pelaporan fiskal, penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif guna memperluas basis pajak. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan DBH Pajak sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia Timur.
AuthorFaisalRizki Aulia HarahapReza RadityaZulhendrizalDownloadOptimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk Mendukung Pembiayaan Pembangunan di Indonesia Timur
PDF File. 828 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 10 : Optimalisasi Dana Perimbangan: Strategi untuk Meredakan Ketimpangan di Indonesia Timur
Upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, khususnya di kawasan timur seperti Maluku dan Papua, memiliki tantangan tersendiri yang belum sepenuhnya dapat teratasi meskipun alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD) telah meningkat secara signifikan. Artikel ini mengkaji efektivitas kebijakan dana perimbangan—meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)—dalam mengatasi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal di kawasan Maluku dan Papua selama periode 2018–2022. Analisis data panel dan uji Granger Causality menunjukkan bahwa meskipun DAU memiliki kecenderungan menurunkan ketimpangan vertikal, secara statistik kontribusinya belum signifikan. Di sisi lain, DBH dan DAK justru cenderung meningkatkan ketimpangan, terutama secara vertikal. Ketimpangan fiskal yang tinggi ini dipengaruhi oleh ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, keterbatasan konektivitas infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang memperburuk kesenjangan. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis merekomendasikan penguatan kapasitas SDM pemerintah daerah, optimalisasi penggunaan TKD, peningkatan PAD, pembentukan Dana Abadi Pertambangan, penerapan pembiayaan kreatif, serta kolaborasi antarwilayah guna mempercepat pemerataan pembangunan.
AuthorAbd. GafurDownloadOptimalisasi Dana Perimbangan: Strategi untuk Meredakan Ketimpangan di Indonesia Timur
PDF File. 828 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 11 : Green Financing sebagai Opsi Utama Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Bagian Timur
Upaya mempercepat pembangunan wilayah Indonesia bagian timur membutuhkan pendekatan inovatif dalam pendanaan infrastruktur. Green financing, sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, muncul sebagai solusi strategis yang dapat menjawab tantangan keterbatasan pendanaan, mendukung pelestarian lingkungan, memitigasi perubahan iklim, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat inklusi sosial. Artikel ini mengkaji urgensi penerapan green financing dalam pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia timur dengan menekankan pentingnya konservasi hutan dan biodiversitas, pemerataan pembangunan wilayah, serta keterlibatan multipihak. Selain itu, artikel ini juga mengulas berbagai instrumen green financing (seperti obligasi hijau, sukuk hijau, pinjaman hijau, dan crowdfunding) serta mekanisme pendukung berupa insentif fiskal dan kerangka regulasi. Potensi pasar kredit karbon juga dibahas sebagai sumber pendapatan baru melalui pendekatan berbasis alam. Penulis menekankan pentingnya kesepahaman antardaerah, penyusunan peta jalan konservasi, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, dan dukungan lembaga donor. Dengan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan, green financing diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pembangunan infrastruktur yang tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga berwawasan ekologis dan sosial di wilayah Indonesia timur.
AuthorFloretta Adriana MamesahNormalita RizkyDownloadGreen Financing sebagai Opsi Utama Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia Bagian Timur
PDF File. 541 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 12 : Skema KPBU sebagai Alternatif Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan di Indonesia Timur
Guna menjawab tantangan keterbatasan pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur, pemerintah memperkenalkan beberapa skema pembiayaan kreatif dan inovatif; salah satunya adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Artikel ini memaparkan potensi KPBU sebagai model pembiayaan yang melibatkan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur publik tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berangkat dari analisis terhadap berbagai proyek KPBU di sektor transportasi, persampahan, air minum, penerangan jalan, dan kesehatan, artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KPBU sangat bergantung pada alokasi risiko yang tepat, regulasi yang mendukung, serta kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang memadai. Berdasarkan analisis kasus di wilayah Indonesia Timur, penulis menekankan pentingnya pendekatan kontekstual yang memperhatikan kondisi geografis dan sosial ekonomi lokal. Untuk itu, penguatan kerja sama multipihak, peningkatan kapasitas lokal, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan KPBU perlu terus diupayakan sehingga KPBU akan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang inklusif dan merata, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal, terutama di kawasan Indonesia Timur.
AuthorDeri FirmansyahDownloadSkema KPBU sebagai Alternatif Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan di Indonesia Timur
PDF File. 545 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 13 : Creative Financing untuk Penyediaan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan di Indonesia Timur
Penyediaan infrastruktur dasar berkelanjutan di Indonesia Timur, misalnya di Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi tantangan yang sangat kompleks akibat keterbatasan fiskal, topografi wilayah kepulauan, dan rendahnya minat investasi swasta. Kesenjangan infrastruktur yang signifikan berpengaruh terhadap rendahnya akses terhadap air bersih, listrik, dan jalan beraspal, serta berkontribusi pada ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Artikel ini mengkaji berbagai skema pembiayaan kreatif (creative financing) sebagai alternatif solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penulis mengeksplorasi model-model pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi hijau, sukuk negara, diaspora bonds, crowdfunding, dan blended finance. Hasil analisis terhadap beberapa kasus, seperti proyek Pelabuhan Tulehu, penyediaan air bersih di Maluku Tengah dan Kepulauan Aru, serta pengembangan energi terbarukan di Pulau Seram menunjukkan bahwa penerapan skema-skema tersebut telah membuahkan dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, keberhasilan implementasi skema pembiayaan kreatif sangat dipengaruhi oleh regulasi yang ada, kapasitas fiskal dan kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Artikel ini merekomendasikan penyusunan kerangka kebijakan yang inklusif dan insentif investasi yang menarik guna menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur.
AuthorZahid Angger PradigdoFahry Friansyah AnasDownloadCreative Financing untuk Penyediaan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan di Indonesia Timur
PDF File. 548 KB 0 DownloadRegister To DownloadChapter 14 : Pembangunan Inklusif di Kawasan Timur Indonesia: Solusi Kesenjangan melalui Peningkatan Kapasitas Daerah dan Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan nasional yang berkelanjutan, Kawasan Timur Indonesia (KIT) perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat wilayah ini masih menghadapi kesenjangan infrastruktur, sosial, dan ekonomi dibandingkan dengan kawasan lain di Indonesia. Artikel yang merupakan epilog “Bersama Memajukan Indonesia Timur: Membangun Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif melalui Skema Pembiayaan Kreatif” ini menyajikan ulasan komprehensif mengenai tantangan, capaian, dan peluang pembangunan di KIT dengan menyoroti berbagai pendekatan pembiayaan inovatif seperti KPBU, green financing, dan optimalisasi dana Transfer Ke Daerah (TKD). Hasil telaah terhadap sektor-sektor strategis, seperti hilirisasi industri tambang, perikanan tangkap, pajak daerah, dan infrastruktur dasar, menunjukkan bahwa keberhasilan percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada alokasi dana, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal. Data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Rasio Gini mengindikasikan adanya perbaikan, namun kesenjangan masih menjadi persoalan nyata yang membutuhkan solusi sistemik. Oleh sebab itu, reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas daerah, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat mutlak untuk mempercepat pertumbuhan wilayah timur secara merata sebagai bagian integral dari visi Indonesia Emas 2045.
AuthorAnton Abdul FatahYuki M.A. WardhanaRatna WidianingrumAndreas WibowoHermawanRoihans Muhammad IqbalDownloadPembangunan Inklusif di Kawasan Timur Indonesia: Solusi Kesenjangan melalui Peningkatan Kapasitas Daerah dan Skema Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Berkelanjutan
PDF File. 390 KB 0 DownloadRegister To Download

Bersama Memajukan Indonesia Timur : Membangun Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif Melalui Pembiayaan Kreatif
Author by IIGF Institute, Talenta Kemenkeu Satu, Universitas Pattimura